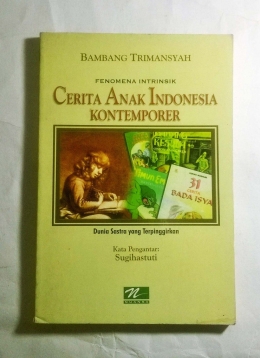Para penulis buku anak riuh di media sosial. Apa pasal? Dewan Juri Sayembara Cerita Anak (SCA) Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) memublikasikan pertanggungjawaban mereka atas keputusan tidak adanya juara I, juara II, dan juara III.
Saya juga ikut berkomentar di Facebook tentang pandangan skeptis adanya buku anak yang bermutu atau memang sangat berpengaruh bagi anak-anak. Di sisi lain pertanggungjawaban Dewan Juri SCA DKJ tersebut mendapat "perlawanan" dari para penulis bacaan anak, terutama mereka yang sudah lama bergabung dalam sebuah grup Facebook bernama Forum Penulis Bacaan Anak.
Mereka sudah menghasilkan puluhan, bahkan ratusan karya buku anak. Terbukti juga buku-buku mereka laris manis serta di antara mereka ada yang menyabet penghargaan nasional dan internasional. Artinya, klaim dari para juri itu tidak sepenuhnya benar dan betul.
Para juri adalah A.S. Laksana, Hamid Basyaib, dan Reda Gaudiamo. Dua orang yang disebut pertama adalah teman diskusi saya saat di Ikapi bersama-sama dengan Mas Hernowo (alm.). Saat berdiskusi di Ikapi, kami merencanakan menerbitkan buku tentang minat baca yang lain daripada yang lain.
Mas Sula (A.S. Laksana), sastrawan mumpuni, sudah menyiapkan konsepnya. Pak Hamid, orang yang sangat bersemangat ketika berbicara buku, kemudian saya ketahui menjadi salah seorang komisaris di perusahaan penerbitan plat merah satu-satunya, Balai Pustaka.
Adapun Mbak Reda Gaudiamo dikenal sebagai seniman dan juga berpengalaman di keredaksian berbagai media remaja. Bahkan, Mbak Reda juga sempat menulis buku anak berjudul Na Willa: Serial Catatan Kemarin.
Para penulis buku anak terutama meributkan paragraf pertama dari isi pertanggungjawaban juri. Saya kutipkan di sini sampai paragraf kedua.
Anak-anak penting bagi banyak orang, dan bagi banyak kepentingan, kecuali bagi para penulis. Para penulis bagus yang kita miliki, atau setidaknya nama-nama yang dikenal sebagai penulis bagus, hampir tidak ada yang menulis buku cerita anak-anak. Mereka merelakan penulisan buku anak-anak kepada orang-orang yang bukan penulis. Mereka mengikhlaskan anak-anak menjalani masa kanak-kanak mereka, yang disebut-sebut sebagai masa emas pertumbuhan, untuk menggeluti buku-buku yang rata-rata ditulis dengan kecakapan seadanya.
Karena ditinggalkan oleh para penulis terbaiknya, dunia penulisan buku anak-anak kita tidak mampu melahirkan tokoh-tokoh fiksi yang bisa melekat dalam ingatan untuk waktu yang panjang, seperti misalnya Peterpan, Pippi si Kaus Kaki Panjang, Alice (dalam Alice in Wonderland), Lima Sekawan, atau belakangan Harry Potter. Mungkin si Doel adalah satu-satunya tokoh anak-anak yang paling kita ingat, tetapi anak-anak sekarang barangkali tidak membacanya. Bahasa yang digunakan oleh Aman Datuk Madjoindo dalam buku Si Doel Anak Djakarta niscaya sudah terasa aneh bagi anak-anak sekarang. (Sumber: Pertanggungjawaban Dewan Juri Sayembara Cerita Anak Dewan Kesenian Jakarta)
Para penulis buku anak senior "meradang menerjang" karena paragraf pertama bagi mereka menggeneralisasi semua yang ikut sayembara adalah sama pun yang tidak ikut sayembara. Apalagi ada kalimat: Mereka merelakan penulisan buku anak-anak kepada orang-orang yang bukan penulis. Mereka mengikhlaskan anak-anak menjalani masa kanak-kanak mereka, yang disebut-sebut sebagai masa emas pertumbuhan, untuk menggeluti buku-buku yang rata-rata ditulis dengan kecakapan seadanya.
Nah, mereka ini siapa? Apakah Andrea Hirata, Dewi Lestari, Eka Kurniawan, A. Fuadi, atau sederet nama sastrawan beken yang dapat dituliskan di sini. Mari kita bahas dengan hati yang sejuk.
Ketika Sastrawan "Turun Gunung" Menulis Cerita Anak
Saya kira paragraf pertama itu adalah sebentuk kesimpulan dari para juri plus juga akumulasi pengalaman mereka menelusuri dunia sastra anak Indonesia selama ini.
Paragraf itu dulu terjawab dalam diskusi saya dengan Mas Wendo (Arswendo Atmowiloto) di Redaksi Koran Tempo. Saat itu, Koran Tempo hendak menurunkan laporan utama tentang buku anak di Indonesia.
Tahun 1970-an dan 1980-an adalah masa keemasan bagi buku anak Indonesia. Para sastrawan turun gunung menulis buku cerita anak. Pada waktu itu, menurut Mas Wendo, sastrawan yang tidak menulis buku anak dianggap belum diakui kesastrawanannya.
Dalam diskusi saya juga mendapat informasi dari Mas Wendo bahwa Todung Mulya Lubis dulu adalah penulis cerita anak di majalah Si Kuncung. Namun, Todung bukanlah sastrawan, melainkan advokat.
Tahun 1970-1980-an memang terjadi booming buku anak karena adanya Proyek Inpres. Proyek Inpres adalah proyek pengadaan buku bacaan anak secara besar-besaran untuk meningkatkan minat baca anak-anak Indonesia.
Waktu itu Indonesia mengalami surplus pendapatan dari minyak bumi. Pengusul proyek tersebut adalah Ajip Rosidi yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia). Lewat pejabat P&K saat itu, ia menyampaikan program ini kepada Presiden Soeharto.
Gayung bersambut, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksinya. Dana miliaran rupian pun digelontorkan untuk pengadaan buku bacaan anak SD. Alhasil, banyak penerbit yang mencari naskah buku anak dan para sastrawan pun terpanggil menulis buku anak.
Saat itu, menurut Mas Wendo lagi, banyak sastrawan yang kaya mendadak.
Beberapa sastrawan yang saya ingat menulis buku anak saat saya meneliti buku anak untuk skripsi tahun 1997 di antaranya Toha Mochtar, C.M. Nas, Titi Said, Djoko Lelono, Dwianto Setyawan, Wimanjaya K. Liotohe, Arswendo Atomowiloto (tentu saja), dan Abdul Hadi W.M. Sederet nama masih banyak lagi.
Pada dekade 1990-an proyek pengadaan buku anak dan produksi buku anak masih menggeliat. Selain dari kalangan sastrawan, para penulis baru pun bermunculan meramaikan proyek ini.
Di sinilah "bencana" mulai terjadi. Siapa pun seolah-olah terpanggil menulis buku anak karena tergiur dana proyek. Siapa pun bahkan dipaksakan menulis buku cerita anak tanpa pengetahuan dan pemahaman sama sekali.
Penulis buku anak yang saya sebut para petualang ini kemudian memenuhi rimba persilatan buku anak Indonesia. Buku-buku bertema monoton lahir seiring dengan tema-tema pembangunan yang digulirkan pemerintah.
Zaman Orba, tema buku seperti Program KB dan GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) bertebaran, lalu diikuti buku-buku antinarkoba, antikorupsi, dan sekarang antiradikalisme.
Banyak juga buku sejenis how to atau 'cara membuat sesuatu' dinarasikan sehingga muncul buku tentang beternak itik, budidaya rumput laut, atau budidaya ikan bandeng dikemas menjadi novel.
Dewan Juri SCA DKJ menyampaikan gugatan mengapa para sastrawan yang sudah "berminyak" dalam menulis karya sastra yang bagus tidak turut membuat buku cerita anak.
Mereka menyayangkan situasi ketika makin banyak penulis petualang tadi. Faktanya memang demikian yang terjadi meskipun tidak semua dari para penulis buku anak yang ada kini adalah para petualang.
Abdul Hadi W.M. yang dikenal sebagai penyair, budayawan, dan pakar filsafat pernah menghasilkan kumpulan puisi anak bertajuk Mereka Menunggu Ibunya. Toha Mochtar pernah menulis buku cerita anak berjudul Si Belang.
Begitu juga Mohammad Sobary suatu ketika pernah menulis buku anak. Saat saya masih bekerja di Salam Prima Media, saya pernah berkunjung ke rumah beliau. Mas Sobary menyerahkan beberapa judul buku anak-remaja yang pernah ditulisnya untuk diterbitkan ulang.

Penulis Cerita Anak yang "Bukan Sastrawan"
Melalui penelitian untuk skripsi yang kemudian saya bukukan dengan judul Fenonema Intrinsik Cerita Anak Indonesia Kontemporer: Dunia Sastra yang Terpinggirkan, saya juga menyajikan opini yang terdengar sumbang apabila dibacakan.
Ada lebih dari 40 judul buku anak yang saya baca dan teliti secara acak periode terbitan 1980-an dan 1990-an. Kesimpulannya minim sekali buku yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai buku yang baik atau bagus untuk anak. Sebagian besar buku adalah buku yang lulus penilaian Proyek Inpres.
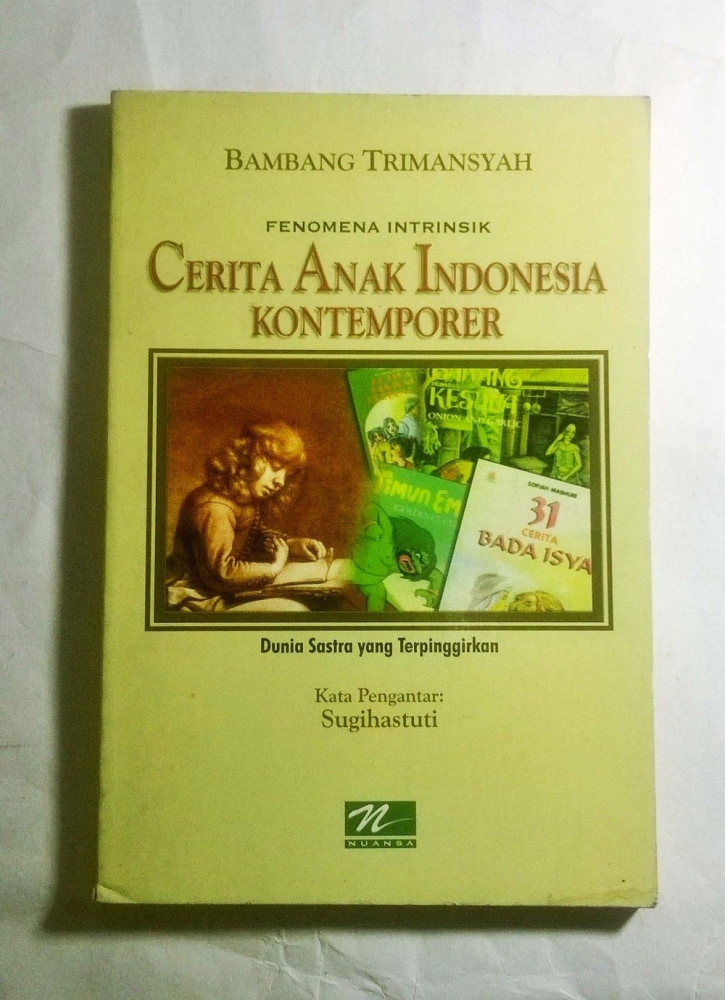
Sampai kemudian lahirlah generasi baru penulis buku cerita anak Indonesia. Saya dapat menyebutkan generasi Ali Muakhir, dkk. Saya sendiri terlibat di dalamnya. Generasi itu mulai meramaikan industri buku anak dengan tema lebih beragam dan lebih maju.
Di antara para penulis itu dapat saya sebutkan di sini, seperti Ali Muakhir, Imran Laha, Tasaro GK, Benny Rhamdani, Ary Nilandari, Iwok Abqari, Dian Kristiani, Watiek Ido, Eva Nukman, Debby Lukito, Agnes Bemoe, Fita Chakra, Sofie Dewayani, Arleen A., dan banyak lagi (ingatan saya terbatas saking banyaknya).
Gerbong paling panjang adalah gerbong Forum Penulis Bacaan Anak yang ditumpangi ribuan penulis buku anak. Lalu, ada lagi gerbong yang ditarik oleh Room to Read (RtR) dan Yayasan Litara yang dimotori oleh Sofie Dewayani dalam beberapa tahun terakhir ini. Di Ubud Writers Festival, karya sastra anak juga mulai mendapat tempat untuk dibincangkan.
Dewan Juri SCA DKJ sebenarnya sedang menggugat mengapa para sastrawan tidak "turun gunung" menulis buku cerita anak. Siapa itu para sastrawan? Apakah para penulis buku cerita anak selama ini tidak dapat disebut sastrawan?
Nah, bagi saya ruang dialog atau mau lebih ekstrem lagi ruang debat harus dibuka untuk soal ini. Apakah seorang Road Dahl tidak dapat disebut sastrawan?
Namun, di satu sisi saya tidak memungkiri bahwa ada tendensi "menggampangkan sastra anak" pada sebagian besar penulis.
Mereka yang kebanyakan masuk ke wilayah sastra anak atau buku anak sekadar coba-coba. Mereka sama sekali tidak mengerti sastra anak dan paham dunia anak-anak. Tentang hal ini saya punya pengalaman juga sebagai juri dan anggota panitia penilaian buku nonteks di Pusat Perbukuan.
Anggap Sebagai Pemantik
Bagi saya laporan pertanggungjawaban Dewan Juri SCA DKJ itu anggap saja pemantik tentang perhatian kita terhadap perkembangan sastra anak Indonesia, dalam hal ini buku bagi anak-anak.
Kita pahami bersama bahwa industri buku anak adalah industri besar yang menghasilkan banyak rupiah, apalagi dengan potensi pasar yang besar.
Namun, harus diakui sebagian besar buku yang terbit masih kalah kualitas dibandingkan buku anak di luar sana. Di ajang Bologna International Book Fair, pameran buku anak terbesar di dunia, penulis buku anak kita mulai unjuk gigi dengan difasilitasi oleh Bekraf dan Komite Buku Nasional. Namun, persoalan unjuk gigi ini tidak menggambarkan persoalan nyata kemajuan sastra anak/buku anak kita.
Kajian-kajian tentang sastra anak minim sekali dilakukan. Buku yang pernah terbit terkait sastra anak dapat saya sebutkan di sini adalah karya Riris K. Toha Sarumpaet (Pedoman Penelitian Sastra Anak/Penerbit Obor), Burhan Nurgiyantoro (Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak/UGM Press), Christantiowati (Bacaan Anak Indonesia Tempo Doeloe/Balai Pustaka), dan juga karya Murti Bunanta tentang cerita rakyat.
Masih ada beberapa buku lainnya juga, tetapi saya kira jumlahnya tidak lebih dari 20 judul.
Sastra anak kita memang dunia yang terpinggirkan dari dahulu--seperti yang saya tuliskan di dalam skripsi dan buku. Para penulis buku anak dibiarkan tanpa pembinaan yang berarti. Sementara itu, gerakan literasi digaungkan di sana-sini. Tak ada guna gerakan literasi itu jika tidak ada buku yang pantas untuk dibaca anak-anak.
Dewan Juri SCA DKJ meskipun hanya bertiga, telah memantik emosi bahwa memang penulis buku anak dianggap sebagian besar belum becus. Alhasil, buku anak yang dihasilkan juga tidak bergema di dalam dunia kanak-kanak negeri ini.
Penulis kita tidak mampu menciptakan karakter (tokoh) yang kuat layaknya karakter yang dciptakan oleh Amerika, Eropa, atau Jepang dan Korea.
Mengambil contoh Jepang, mengapa penulis kita tidak mampu menciptakan semacam Doraemon, Kapten Tsubasa, atau Sailor Moon? Mengapa yang masih tertancap kuat adalah tokoh Si Unyil dkk. dan Si Komo?
Soal ini sudah pernah juga saya gugat, tetapi harus disadari lahirnya karakter-karakter kuat itu karena industrinya memang mendapat dukungan dari pemerintah. Kemunculan sebuah karakter dalam bentuk buku harus didukung dengan alihwahana lainya, yaitu film animasi, gim (game), bahkan juga produk pernak-pernik.
***
Saya kira diperlukan semacam kajian mendalam, ruang-ruang diskusi yang intens, atau apa pun namanya untuk mengembangkan strategi melahirkan para penulis buku anak yang mumpuni.
Mereka tidak dapat lahir tiba-tiba seperti halnya J.K. Rowling yang sudah terdidik dalam pendidikan bahasa dan sastra bermutu. Sebagai anggota panitia penilaian buku nonteks sejak 2017 di Pusat Perbukuan, saya sendiri sudah cukup mengurut dada, leher, dan kepala melihat buku-buku yang dinilaikan.
Mau mencari kambing hitamnya siapa? Tidak jelas karena sang kambing hitam sudah mengecat bulunya menjadi belang tiga.[]
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

![Selalu Ada Solusi Memiliki Buah Hati bersama Sang Ahli [Review Buku]](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/06/06/1-kesuburan-68425e16c925c4624f78cee2.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)