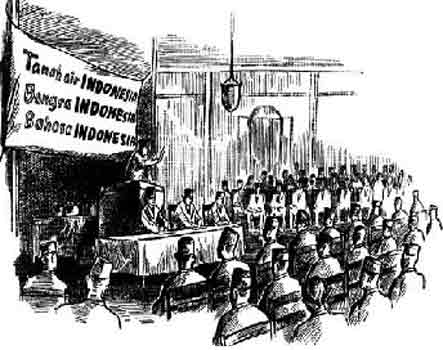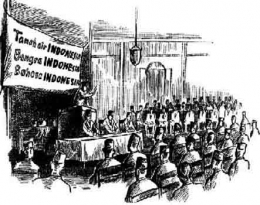[caption id="attachment_274436" align="aligncenter" width="443" caption="(Sumber gambar: http://dpd.go.id)"][/caption] Salah satu masalah yang sering disinggung dalam kehidupan demokrasi di Indonesia adalah kurangnya ruang-ruang untuk mewadahi aspirasi masyarakat. Demikian pula yang terjadi kepada suara-suara pemuda (pelajar dan mahasiswa) yang seringkali didengung-dengungkan sebagai agen perubahan. Gerakan pemuda di tahun 1928, 1966, 1984, dan 1998 bisa jadi menjadi petunjuk penting bagaimana pemuda dapat berperan cukup berarti dalam mendorong perubahan besar dalam sejarah. Namun, pemuda, yang di masa lalu memiliki daya tawar dan daya tekan yang kuat terhadap kekuasaan, belakangan ini semakin tidak memiliki wibawa terhadap kekuasaan. Bisa jadi, gejala “degradasi” ini disebabkan oleh perkara ruang publik yang semakin terhimpit oleh kepentingan-kepentingan ekonomi media massa. Di sisi lain, semakin terkooptasinya media massa dengan aktivitas politik praktis semakin mendorong sempitnya ruang bagi wadah-wadah aspirasi pemuda. Pertama, bahwa media-media massa arus utama–sebagai kelompok media mayoritas–yang lebih populer dan mampu menjaring lebih banyak khalayak, justru abai dengan fungsi yang seharusnya ia perankan. Alih-alih memainkan peran sebagai institusi sosial, sebagai institusi di luar kekuasaan yang turut mendorong nuansa-nuansa demokratis, media massa arus utama kini lebih condong sebagai sebuah industri, sebuah institusi ekonomi. Sebagai institusi ekonomi, maka perhitungan yang dilakukan oleh media massa hanya berkutat pada perhitungan untung-rugi semata. Konsekuensinya, fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan kultur (nilai dan norma), yang seharusnya dilakukan oleh media massa, lepas. Ruang publik tergadai oleh kepentingan ekonomi. Khalayak pun diabaikan. Dalam keadaan yang demikian, khalayak hanya dipertimbangkan hanya ketika media massa (lagi-lagi) memperhitungkan untung-rugi. Khalayak hanya diukur sebagai jumlah sekumpulan massa yang ditawarkan kepada pemodal dan pengiklan, tanpa mengukur persepsi dan perasaan khalayak terhadap media. Dalam keadaan yang demikian pula, sebenarnya, bukan hanya suara pemuda yang tidak terwakili di ruang-ruang publik, tetapi juga suara banyak masyarakat. Dalam suatu diskusi terbuka di kampus, saya tertarik pada pendapat yang dikemukakan oleh salah seorang narasumber yang merupakan aktivis mahasiswa. Narasumber tersebut mengajukan alasan mengapa aksi mahasiswa di Sulawesi Selatan, daerah yang sangat jauh dari pusat kekuasaan nasional, hampir selalu berakhir dengan aksi-aksi kekerasan. Menurutnya, perkaranya hanya satu, bahwa mereka hanya ingin pendapat mereka didengar. Mereka ingin apa yang mereka sampaikan dapat ditangkap oleh khalayak nasional. Meskipun alasan ini tidak serta merta dapat diterima sebagai pembenaran, tetapi alasan ini cukup logis. Selama ini, daerah memang hampir tidak tersorot oleh media-media nasional. Daerah dipertimbangkan dalam ruang redaksi untuk dikabarkan, (hampir selalu) hanya jika terjadi aksi-aksi kekerasan di daerah. Tentu saja ada alasan sendiri bagi media untuk mempertimbangkan hal ini: pertimbangan ekonomi. Untuk apa menampilkan berita yang tidak bombastis, yang pada akhirnya tidak menarik khalayak untuk menyimak konten media? Kedua, keadaan yang cukup memprihatinkan bagi iklim demokrasi ini, ternyata justru diperparah dengan masuknya kepentingan-kepentingan politik praktis di tubuh media massa. Cukup nampak jelas bahwa di Indonesia, pemain-pemain besar media adalah orang-orang yang ”superior” secara ekonomi maupun politik, dengan penguasaan jejaring dan persilangan media yang telah menggurita. Tentu saja, gejala-gejala semacam ini menambah ancaman terhadap peran media massa dalam mendorong demokratisasi. Bahwa pertimbangan ekonomi menjadi pertimbangan yang cukup penting untuk memelihara keberlangsungan media. Namun, kepentingan politis terkait pencitraan diri pribadi dan kelompok politik pemilik media atau orang yang dekat dengan pemilik media menjadi tekanan yang begitu kuat terhadap ruang publik yang difasilitasi oleh media massa. Karena itu, untuk menyelesaikan perkara ini, khususnya terkait peran media sebagai ruang publik untuk mewadahi aspirasi pemuda (pada khususnya), diperlukan transformasi terhadap sistem. Bahwa jika media ternyata sudah tidak mampu dan tidak lagi berperan sebagaimana mestinya sebagai institusi sosial yang mendorong terciptanya iklim demokratis, perlu adanya gerakan (re)demokratisasi sistem media. Di sisi lain, pemuda juga harus mulai memikirkan “media-media lain” sebagai penyalur aspirasi mereka dalam konteks partisipasi politik. Karena, perlu dipahami pula bahwa dalam demokrasi, media massa hanya satu dari banyak saluran yang dapat digunakan oleh warga negara untuk terlibat dalam proses politik. Selamat hari sumpah pemuda, para pemuda Indonesia. Mari bergerak!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H