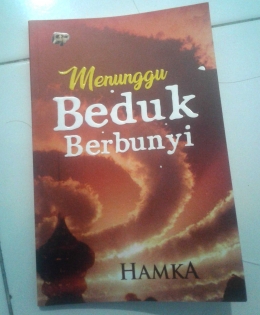Tak ada yang meragukan karya sastra HAMKA. Saya juga menyukai beberapa novel beliau yang sudah di film kan. Apalagi sejak mengenal Ustadz Abdul Somad Lc. MA di Youtube, yang juga sama-orang Melayu, saya jadi semakin penasaran dengan karya-karya HAMKA yang lain. Setelah saya browsing, ternyata banyak sekali novel yang telah ditulis . Ternyata saya yang kudet.
Beberapa waktu yang lalu, saya ke toko buku, penasaran dengan buku yang berjudul "Menunggu Beduk Berbunyi", sebuah novelet (novel pendek) beliau yang isinya dua judul : "Dijemput Mamak" dam "Menunggu Beduk Berbunyi".Buku mungil ini hanya 118 halaman dengan harga hanya 30 ribuan, tapi isinya sangat mengenyangkan hati dan pikiran.
Jujur sebelum membeli buku ini, saya belum membaca reviewnya. Padahal biasanya saya sering mencari info dulu di google kalau mau beli buku baru. Tapi ketika membaca ringkasan cerita di cover belakang, saya sudah tertarik karena dua cerita ini berlatar belakang masa penjajahan dan masa kemerdekaan. HAMKA memang benar-benar bisa menggambarkan suasana pada masa itu, era tahun 30 an, 40 an, sampai 60 an. Semua seperti begitu nyata.
Cerita yang pertama "Dijemput Mamak" adalah kisah Musa yang berprofesi sebagai tukang ganti kain kasur yang telah rusak. Karena keadaan ekonomi yang terpuruk, berpengaruh juga dengan ekonomi keluarga yang pada akhirnya harus menemui keputusan keluarga besar istrinya yang menyuruh istrinya untuk pulang. Dan kenyataan pahit harus di rasakan Musa - bercerai dengan istrinya. Pahit, pedih, karena keluarga besar ikut dampur dalam urusan rumah tangganya. Kisah ini semacam kritik , bukan saja untuk orang Melayu tapi untuk semua orang yang mengagungkan harta dunia . Bahwa kebahagiaan tidak selalu berbentuk uang.
Meskipun ada beberapa kata yang tidak saya mengerti karena kental bahasa Melayu, tapi saya menikmati saja sebagai keunikan buku ini. Seperti kata dukuh paun ringgit atau kalimat bagai melantamkan bedil pecah .
Cerita kedua "Menunggu Beduk Berbunyi" tentang seorang mantan pegawai Belanda yang sudah tobat, tapi tetap saja dimusuhi oleh orang-orang pribumi. Mereka marah karena kelakuannya (dianggap) sangat tidak beradab. Ketika orang-orang kelaparan, tapi dia senang-senang dengan fasilitas yang diberikan Belanda.
Pada suatu titik, memang dia sadar bahwa sikapnya sangat tidak pantas. Tapi itu semua dilakukan karena terpaksa keluarganya yang kelaparan. Tak ada lagi makanan yang ada di rumah. Semua serba kekurangan. Kenyataan yang didapat sekarang sangat menyakitkan. Hidup sendiri, tak ada teman dan saudara yang mendekat dan dia hanya butuh belas kasihan orang yang sedang marah padanya.
Suatu saat dia mendengar khutbah Jumat yang membahas tentang puasa Ramadan. Setiap orang Islam harus sabar menunggu beduk berbunyi untuk berbuka puasa. Dia merasa tertonjok, tidak sabar menunggu saatnya kemerdekaan Indonesia tiba. Dia sangat merasa berdosa.
HAMKA menutup cerita itu dengan sangat menyentuh, "Marah adalah kebiasaan banyak orang.Akan tetapi belas kasihan adalah kebiasaan orang yang utama."
Sungguh novel ini mengajak kita untuk bicara dengan hati nurani kita sendiri. Bagaimana menata hati, dan HAMKA memberikan terapi menghaluskan hati .
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H