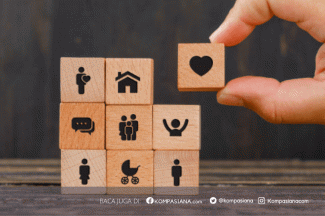Pengakuan akan eksistensi diri sudah menjadi kebutuhan manusia sejak dahulu kala. Bahkan Mashlow sudah menyampaikan nya dalam teori hirarki, salah satu kebutuhan puncak yang tiada habisnya adalah aktualisasi diri. Maka dari itu, tidak heran manusia selalu ingin menunjukkan keberadaannya di bumi ini. Semenjak kemajuan teknologi, eksistensi manusia pun terus meluas dan begitu mudahnya manusia mendapatkan pengakuan. Media sosial memfasilitasi perilaku ini dengan sangat baik. Dulu ketika kita membeli mobil baru, hanya tetangga kita yang tahu, tapi sekarang bahkan penduduk di ujung bumi pun bisa mengaksesnya melalui profil media sosial kita. Kemudahan semua orang mengakses tentang segala hal mengakibatkan kita juga tidak ingin kalah dibandingkan mereka. Hal ini terus menyuburkan hedonisme di dunia modern.
Hedonisme adalah ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Begitu mudahnya seseorang memamerkan kesenangan yang ia ingin tampilkan. Celakanya hal ini memberikan efek domino bagi mereka yang tidak mawas diri, mereka yang tak mampu membedakan mana kebenaran utuh dan kebenaran sebagian. Secara tak langsung mereka pun akan segera menciptakan kebenaran semu nya. Sudah bukan hal yang asing untuk berfoto selfie menggunakan latar belakang kaca kamar mandi mall yang lebar sambil memamerkan lambang buah-buahan di belakang handphone nya. Bahkan tak jarang mereka rela berfoto selfie dengan KTP (read : pinjol) hanya untuk membeli barang-barang bermerek yang menempel di badannya. Perkara nametag karyawan saja sekarang semua berlomba-lomba menjadi yang terdepan untuk bisa mewadahi nya dengan mewah. Yang mirisnya gaji para karyawan dengan lanyard mewahnya hanya setipis UMR.
Jaman dahulu orang yang dianggap kaya adalah mereka yang memiliki tanah yang banyak, dengan ternak yang banyak. Bisa jadi baju mereka sederhana, mobil juga sudah lebih dari 10 tahun tidak diganti, kemana-manapun masih berjalan kaki atau naik motor. Namun, sekarang orang dikarenakan ingin dianggap kaya, aset-aset semacam itu jadi tak ada artinya. Alasannya simple, karena barang-barang seperti rumah merupakan aset tak bergerak, yang tak mudah diketahui oleh orang banyak. Berbeda dengan handphone yang setiap saat kita bisa membawanya. Semua orang pasti tahu apa handphone kita, tapi tak tahu berapa luas tanah kita. Toh rumah dengan luas tanah 90 dan 70 tak nyata kelihatan mata orang awam, meskipun selisih harganya entah bisa beli berapa banyak handphone flagship yang begitu dibanggakan.
Sebuah ironi ketika mobil 500 juta dianggap orang kaya, sementara orang dengan rumah di satelit jakarta tipe 36 dengan harga yang sama bisa dikatakan miskin. Apalagi yang lebih miris adalah ketika seseorang dengan h*nda be*t dianggap miskin sementara seseorang yang setiap harinya mengandalkan ojek online dan krl selama menggunakan iph*ne 15 dengan harga yang sama justru dianggap kaya. Pola pemikiran dangkal seperti ini mengerikan untuk masa depan. Hanya memperhatikan apa yang terlihat, tidak heran Indonesia masih menjadi lahan subur untuk judi online hingga investasi bodong.
Kekayaan bukanlah sebuah tujuan yang salah, yang salah adalah ingin terlihat kaya. Karena mata kita selalu terbatas, tak bisa melihat 360 derajat, dan bahkan sesederhana membukanya terjaga 24/7 pun kita tak mampu. Biasakan untuk menyadari keterbatasan kita dan bersyukur atas apapun yang kita miliki. Kesadaran akan keterbatasan akan membangun sifat mawas diri yang baik untuk dunia yang semakin jahat ini.