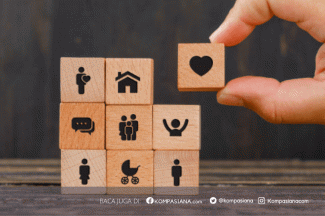Euforia masyarakat begitu besar ketika memasuki bulan Desember. Di sana-sini masyarakat sibuk mempersiapkan banyak pernak-pernik Natal guna menghiasi rumah menjadi indah dan elok dipandang.
Tidak hanya itu, dentuman petasan, bisingnya jalanan karena banyak anak muda memodifikasi knalpot motor mereka dari biasa ke yang racing juga kerap disimbolkan sebagai Natal sudah di depan mata.
Perayaan Natal kini telah dijajah oleh spirit konsumerisme, kapitalis. Bagi yang bermodal, fasilitas Natal tersedia begitu rupa.
Melalui anggapan ini, mungkin para pembaca akan sedikit terusik dengan gambaran keberatan ini, tetapi bagi penulis perayaan Natal bukan soal euforia tetapi pada bagaimana Natal itu membekas dalam diri yang mendorong aksi nyata.
Euforia sifatnya sementara. Ia meletup tiba-tiba, lalu seketika kembali hening. Jangan sampai kemudian perayaan Natal juga sifatnya musiman saja.
Jelang Desember hingga akhir Desember gempita, lalu kemudian kembali redup.
Prasangka ini hidup dalam kebiasaan masyarakat.
Natal tidak lagi bicara soal kasih dan kepedulian yang paripurna, tetapi sekadar pengisi kalender hari raya gerejawi.
Jika demikian duduk masalahnya, maka bagaimana seharusnya kita merayakan Natal?
Sehari sebelum tulisan ini diterbitkan, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt. Jacky Manuputty menegaskan bahwa esensi perayaan Natal adalah kesederhanaan.
Konsep hidup sederhana atau dalam istilah teologisnya ugahari telah lama diperbincangkan.
Gereja dan para pemimpinnya banyak bersuara untuk jangan terjebak dalam spirit euforia tetapi hasilnya selalu nihil.