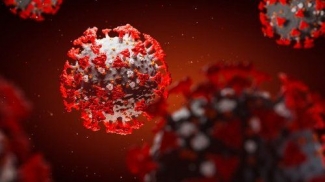Sejak wabah virus corona merebak di Wuhan Tiongkok dan menyebar ke berbagai belahan dunia, kita seringkali mendengar atau membaca berita-berita, komentar-komentar atau pernyataaan banyak politisi, pemimpin dan pejabat negara memakai metafora perang atau kata-kata yang berkonotasi perang untuk menjelaskan tantangan yang kita hadapi.
Donald Trump, Presiden Amerika Serikat menggambarkan dirinya sebagai presiden masa perang, berperang melawan musuh yang tak terlihat. Di dalam pidatonya 5 April yang lalu, Ratu Elizabeth II dari Britania Raya kembali membangkitkan sebuah lagu Perang Dunia II. Begitu pula Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte juga demikian membangkitkan suasana perang dunia ke II di dalam upaya negaranya menanggulangi wabah pandemi covid 19 ini.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutierrez dalam kata sambutannya dalam KTT virtual G20 mengatakan: "We are at war with a virus . And This war needs a war-time plan to fight it."
Rodrigo Duterte, Presiden Filipina dalam keterangan Persnya terkait kebijakan lockdown yang dia terapkan, " Kita berperang melawan musuh yang ganas dan tidak terlihat. Dalam Perang yang luar biasa ini, kita semua adalah prajurit.
Di Indonesia, Presiden Jokowi juga mendeklarasikan hal yang sama dalam pidatonya atau instruksinya kepada jajaran di bawahnya dengan bahasa yang sama yaitu Perang melawan virus corona.
Nah, Dari semua pidato-pidato, komentar-komentar dan percakapan-percakapan seputar pandemi tersebut kita mendapatkan metafor-metafor yang berkonotasi perang yang sering kita dengar dan kita baca baik yang eksplisit seperti "Kita sedang Perang," maupun yang implisit seperti " musuh tak terlihat, ancaman, garis depan, pertempuran, dan sebagainya.
Perumpamaan seperti sedang perang ini terlalu memaksakan, Di dalam perang harus ada musuh (yaitu virus), pejuang-pejuang garis depan (yaitu tenaga medis), garis belakang (orang-orang yang mengisolasikan diri di rumah), pengkhianat yaitu orang-orang yang melanggar aturan social/physical distancing. Bahkan bahasa biomedis dan epidemilogi juga sudah dimilterisasi seperti "Kami 'memerangi' virus" dan "Tubuh kita memiliki mekanisme 'pertahanan' melawan patogen yang 'menginvasi' nya.
Memang metafor perang ini sangat menarik sebagai sebuah alat retorika politik, namun ia menyembunyikan perangkap, di dalam kasus pandemi Covid 19, bisa berbahaya.
Perang adalah bisnis negara. Beberapa orang berargumen peranglah yang sesungguhnya membentuk negara moderen. Penggiringan respon terhadap COVID 19 di dalam bahasa militer akan memperkuat pemikiran statis semacam itu. Ia akan memperkuat negara dan kekuasaannya.
Adalah benar adanya bahwa tatanan politik yang berlangsung saat krisis menghantam, negara memegang banyak kapasitas organisasional dan kekuasaan. Ia memiliki sebuah peranan krusial untuk berperan dalam menangani keadaat darurat pada saat belakangan ini. Namun ini bukan cuma menjadai masalah negara saja, namun juga menjadi masalah entitas-entitas politik lainnya juga, dari jaringan-jaringan spontan bottom-up, dari organisasi-organisasi tingkat kota sampat tingkat regional, bahkan sampai internasional seperti WHO. Metafora-metafora berkonotasi militer pada akhirnya membungkus kontribusi-kontribusi mereka dalam istilah-istilah militer.
Krisis ini bukan melulu soal medis kedokteran, pekerja kesehatan dan masyarakat manusia di seantero dunia, tapi juga soal-soal seputar kelas-kelas sosial-ekonomi, seperti para pekerja pasar swalayan, pekerja pengiriman barang dan pabrik-pabrik perlengkapan yang esensial, di semua negara yang menderita akibat virus. Melihat kepada kelas-kelas sosial-ekonomi lintas batas juga bisa membuat lebih banyak diskusi-diskusi mengenai kelompok masyarakat tunawisma, tempat-tempat pengungsi, syarat-syarat kerjadan perawatan kesehatan universal. Dan daripada memperkuat pemikiran statis militer, lebih banyak faedah menjelaskannya dengan misalnya istilah-istilah marxis, feminis, anarkis, atau liberal internasionalis.