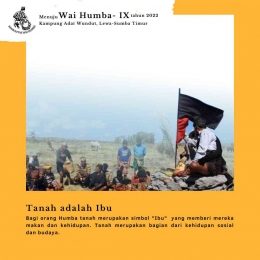Kami akan makan malam. Sudah larut. Menjelang pukul 22.00 waktu di Sumba. Makan malam yang terlambat. Tetapi mengurus seribuan orang yang datang dari seluruh pelosok Pulau Sumba untuk mengikuti Festival Wai Humba IX perlu tenaga ekstra. Dan memasak bahan yang banyak. Apalagi Kampung Adat Wundut di Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, NTT, tempat acara diselenggarakan sejak siang diguyur hujan. Jalanan yang mendaki menuju kampung telah becek dan licin. Banyak kendaraan kandas. Seluruh peserta baru berkumpul sejam sebelum makan malam itu.
Di depan saya berjarak satu meter, pada bale-bale rumah adat itu, adalah Pater Mikael Molan Keraf, CsSR (53). Ia duduk bersila.
Sementara di samping saya Bapak Ngongo Gaddi (70), Rato Marapu (pemimpin tertinggi agama Marapu) dari kaki Gunung Yawila di Sumba Barat Daya (SBD).
Saya dan Mike membuat tanda salib untuk memulai santap malam. Bapak Ngongo Gaddi mengangkat piringnya sejenak, memejamkan mata dan bersantap.
"Saya yang kasih tanah untuk bikin Gua Maria di Yawila itu. Sekitar dua hektar," kata Ngongo Gaddi usai santap malam. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia bercampur bahasa Waijewa, suku asalnya. Saya minta dia berbicara saja dalam bahasa Waijewa. Saya bisa memahami maksudnya. Saya bisa berbahasa Waijewa dan tentu saja, Kodi. Dua bahasa ibu suku besar di SBD.
Gua Maria identik dengan agama Katolik. Ngongo Gaddi seorang penganut Marapu.
"Kenapa Bapak mau kasih tanah buat umat Katolik?" tanya saya.
"Karena Tuhan kita hanya satu. Hanya cara menyembahnya yang berbeda-beda," ujarnya tandas.

Saya terhenyak. Ternyata kearifan dan kecerdasan dan keinginan hidup berdampingan secara damai tak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan.
Bapak Ngongo Gaddi tak pernah sekolah. Tak kenal baca tulis. Buta huruf total. Hanya bisa berbahasa Indonesia karena sering berjumpa orang luar. Juga karena sanak saudaranya banyak yang bersekolah tinggi.