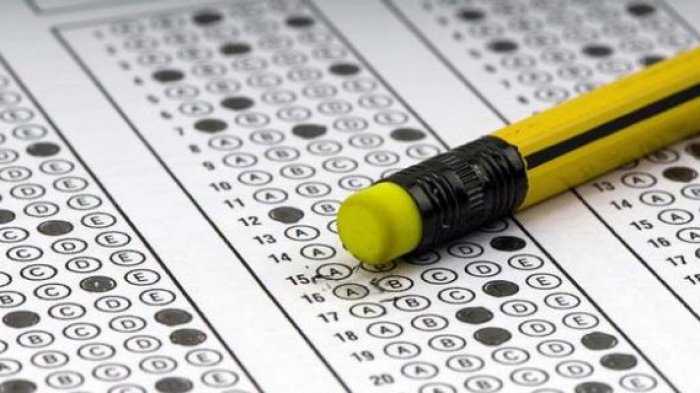Musim libur sekolah sudah tiba. Lega rasanya. "Penjara" bernama sekolah membebaskan guru dan siswa untuk menghirup udara segar di luar. Tidak mikir ulangan harian, bebas dari tugas analisis soal, rehat sejenak usai ngaji alias ngarang biji untuk nilai rapot. Dua minggu libur sekolah yang bertepatan dengan libur akhir tahun bagaikan seteguk air dingin di tengah padang pasir yang terik.
Buku rapot siswa untuk sementara lebih baik dikunci dalam lemari. Deretan angka-angka yang tidak perlu terlalu serius diperhatikan. Para orangtua sebaiknya rileks saja---angka yang tertera di rapot itu pada kadar tertentu mengandung "hoax". Logika Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tak lebih sebuah dagelan akademis. Walaupun ada rumus baku untuk menentukan KKM mata pelajaran, semoga para guru tidak menuliskannya cukup berdasar bisikan intuisi atau ilham dari Tuhan.
Telah menjadi rahasia bersama bahwa KKM adalah penyelamat kinerja guru, penentu masa depan siswa, pelipur hati para orangtua. Nilai mata pelajaran harus minimal sama dengan KKM. Kecuali guru tersebut merelakan diri untuk berpayah-payah meladeni protes orangtua siswa. Siap dituduh "makar" oleh pimpinan sekolah. Rela dikalungi label guru tidak profesional. Dengan segala hormat dan sikap mulia, guru harus mematuhi gurita kepentingan regulasi sekolah.
Pragmatisme menjadi jalan keluar. Yang penting guru aman sehingga situasi nyaman yang dipelihara secara berjamaah dan menjadi komitmen bersama itu akan saling menyelamatkan.
Kita tidak perlu mengelus dada. Semua itu wajar. Diamini secara diam-diam, mulai guru, kepala sekolah hingga pimpinan dinas pendidikan di kota itu. Namun, kita jangan menuntut bukti fisik atas praktik pemberian "nilai-hoax" di rapor. Berkas administratifnya sangat sempurna. Tidak perlu berlagak akademis. Semua pihak merasa senang dan aman. Sekolah pun diuntungkan.
Belajar di sekolah memang menyenangkan. Guru sudah sejahtera berkat tunjangan sertifikasi. Ekonomi mapan. Tidak pusing besok bisa makan apa tidak. Siswa pun tak kalah bahagia. "Santai saja. Nilai di rapor pasti minimal sama dengan KKM." Bisik-bisik seperti itu kencang beredar di antara siswa. Tidak ada yang lebih membahagiakan siswa selain belajar "ala kadarnya" lalu nilai akhir yang muncul di rapor melompat naik.
Saling berbagi bahagia---adakah yang lebih mulia dari itu semua? Sekolah adalah taman kebahagiaan. Berbunga optimisme menatap masa depan. Berbuah senyum yang merekah.
Pendidikan kita sarat dengan eufemisme yang terstruktur. Visi misi yang diusung bagus-bagus. Mentereng. Tema yang dijual pun beragam: cerdas dan berakhlak mulia, generasi qurani, jaminan hafal Al-Quran 10 juz. Seakan-akan siswa adalah barisan makhluk mekanik yang digerakkan oleh logika linier angka-angka.
Standarisasi kompetensi wajib hukumnya. Mereka tidak dididik agar menggunakan nalar sehat, karena paket-paket cara berpikir telah disiapkan sebelumnya. Siswa tinggal menelannya.
Sekolah tidak menempatkan diri sebagai bagian integral dari dinamika perubahan, kecuali sebatas persoalan teknis seperti penggunaan teknologi informasi. Adapun peta persoalan yang memerlukan sofware berpikir dan bersikap, sekolah mengalami dislokasi dan disorientasi. Sekolah memasang papan tulis pendidikan yang terlepas dari persoalan kehidupan. Lingkungan belajar jadi terisolasi atau bahkan sengaja mengisolasi diri.
Maka, prestasi dan "prestasi" adalah dua kenyataan yang berbeda. Bagi generasi yang mengalami krisis eksistensi, akibat dari nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran bebrayan yang dilandasi oleh humanisme tidak menyentuh mekanisme software berpikir, mereka cenderung mengejar "prestasi"---dengan tanda petik. Salah satu "prestasi" itu adalah gagap mengidentifikasi berita hoax.