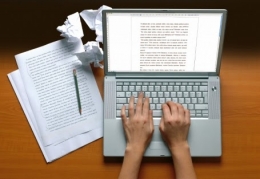Pada pertemuan yang dihadiri para pegiat gerakan literasi, saya diberondong sejumlah pertanyaan terkait kegiatan menulis. Mulai dari bagaimana kiat praktis menulis, kapan waktu yang tepat menuangkan gagasan dalam tulisan hingga mengapa saya memilih Kompasiana untuk mewadahi tulisan-tulisan saya?
Atas semua pertanyaan itu saya menyampaikan, “Saya bukan pakar yang bisa membedah kegaiban yang menyelimuti pikiran teman-teman.” Posisi dan situasi psikologis saya tak jauh berbeda dengan siapa saja yang sedang belajar menulis—saya adalah penulis pemula, akan menjadi penulis pemula, dan bisa jadi selalu menjadi penulis pemula.
Plong Rasanya!
Perasaan yang selalu saya rasakan setelah merampungkan sebuah tulisan adalah plong. Lega bukan main. Ada semacam tekanan dari dalam diri: ide, gagasan, sikap, nuansa, entah apa lagi namanya, ibarat proses sebuah janin ia tumbuh dan berkembang dalam rahim hingga tiba waktunya untuk lahir. Lalu jadilah sebuah tulisan.
Begitu tulisan lahir, merasakan plong sesaat, selanjutnya saya kembali berada di situasi nol. Saya segera melupakan tulisan itu, merasa belum berkarya dan belum menulis apa-apa. Saya akan memulai lagi dari angka 1, 2, 3…8, 9 dan kelahiran sebuah tulisan adalah tahap ke-10. Pada konteks kesadaran ini saya selalu merasa menjadi penulis pemula.
Kalau proses internal itu kita simulasi, sesungguhnya kita sedang melakukan perjalanan yang tidak benar-benar berangkat dari situasi angka nol. Tahap ke-10 adalah sekaligus langkah ke-0 bagi awal perjalanan yang akan beranjak masuk pada tahap satu, dua, dan seterusnya.
Dialektika internal yang terjadi pada proses kreatif menulis melingkar-lingkar dalam jalur gerakan yang linier. Terjadilah gerakan spiral—dan apabila kita potret secara long-shot akan membentuk lingkaran pula. Artinya, seorang penulis tidak boleh dan tidak mungkin berhenti. Proses terjadinya gerakan spiral itu menerbitkan kesadaran tidak ada kutub yang berseberangan antara Aku Penulis Mapan dan Engkau Penulis Pemula.
Stagnasi, kebekuan, kejumudan, kotak-kotak takhayul kebudayaan adalah musuh dalam selimut dan bisa membunuh “kemanusiaan” penulis saat itu juga. Sebutan cerpenis, penyair, kolumnis, atau lebih luas lagi seperti agamawan, ekonom, politikus, ilmuwan, rohaniawan diperlakukan secukupnya saja sebagai identitas sosial terkait teknis rubrikasi atau pekerjaan beberapa jam, tanpa kita sendiri harus meyakini bahwa sebutan teknis itu adalah Diri kita.
Penulis adalah pekerjaan beberapa menit—sebelum dan sesudahnya ia bukan selalu penulis. Ia bisa apa saja: guru, ayah, ibu, ketua takmir masjid, warga RT, pengantri nasabah bank, penumpang bus kota. Situasi di luar aktivitas menulis itu justru menjadi benih, atau semacam proses bertemunya sel telur dan sperma yang tumbuh dan berkembang dalam rahim kreativitas penulis. Dari rahim itu akan lahir “bayi” karya tulis.
Menghayati Getaran dan Aliran
Seorang penulis akan menghayati bahwa hidup adalah getaran yang mengalir dan aliran yang bergetar. Berhubung penulis adalah manusia, maka ia akan selalu bergetar dan mengalir, mengalir dan bergetar dalam dekapan ruang dan laju sang waktu. Getaran dan aliran itu tidak bisa dibendung atau dihalangi oleh sekat-sekat primordialisme yang mencampakkan dialektika alamiah sebagai manusia.